Belajar dari Sokrates, Michel Foucault hingga Rocky Gerung
“semuanya menjadi sedikit berbeda segera setelah diucapkan dengan lantang” Demikian ungkapan Hermann Hesse seorang peraih Nobel bidang Sastra pada tahun 1946.
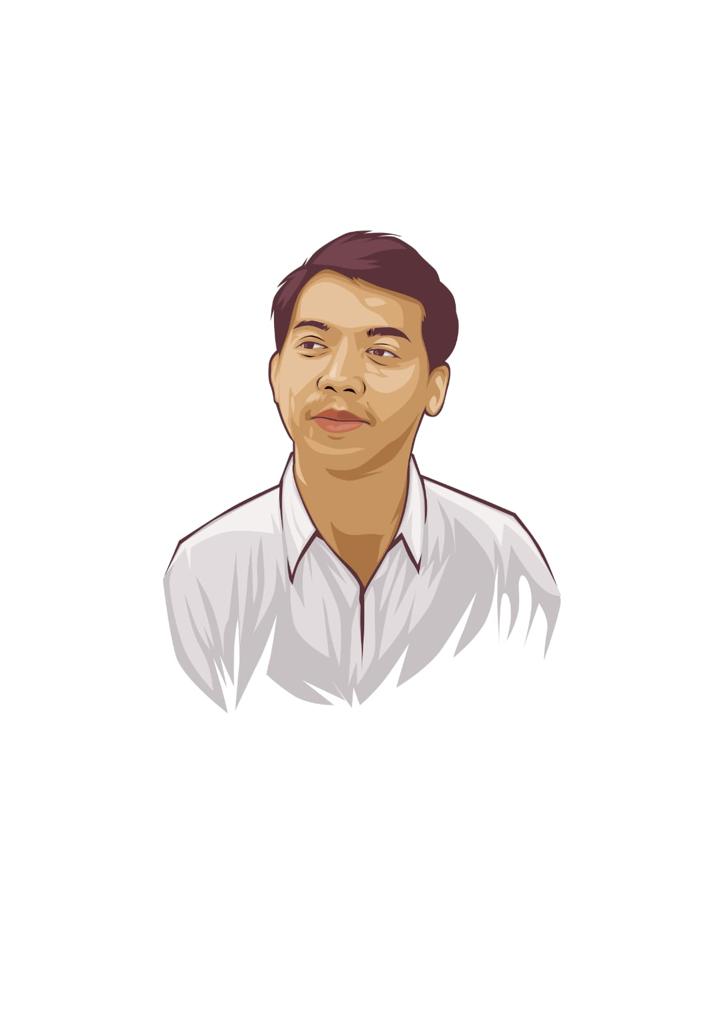
Kalimat Hermann Hesse di atas segaris lurus dengan ungkapan dari seorang pengamat yang menguncang dunia politik junto Intelektual beberapa waktu lalu. Ungkapannya bak anak panah lepas dari busurnya dan tertancap tepat pada jantung kekuasaan di negeri ini ( baca : Presiden RI)
Ungkapan Rocky Gerung (RG) terhadap Presiden Jokowi bukan selentingan spontan. RG acap kali melontarkan kalimat-kalimat tajam di berbagai pidato dan ceramahnya. Ia seringkali menyampaikan bahwa “Sopan santun di dalam politik adalah kemunafikan”. Artinya : ia jujur dan sadar menyampaikan buah pikirnya sebagai sikap kritis atas kerja-kerja pemerintah.
Di sisi lain, Presiden Jokowi menanggapi RG dengan sangat tenang.
“itu hal kecil, saya kerja saja”. Kata Presiden jokowi.
Beda Presiden Jokowi, beda loyalisnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai relawan Jokowi telah menempuh jalur hukum. Memang sih, relawan kadang kala lebih rela dari yang dibelanya. Namun, reaksi seperti ini justru bisa memantikkan api polarisasi. Faktanya ; fanatisme kerelawanan merupakan satu sikap yang acap kali mengaduk suasana kebatinan politik kita.
RG telah memilih dan menawarkan gramatika politik yang berani. Hanya saja, selain kosakata itu berhadapan dengan kekuasaan juga berhadapan dengan etika umum masyarakat. Walaupun RG menuturkan untuk kepentingan kritisisme tetapi tidak bisa menghindari interpretasi umum ; pilihan diksinya tidak sopan, kurang ajar dan cenderung bernuansa hinaan.
Hemat saya, secara leksikal pernyataan RG sangat Kurang ajar. Tetapi secara ilokusif sebaiknya setiap pernyataan dicermati konteksnya. Jika melihat keseharian penutur sepertinya kalimat itu memiliki maksud kritis sebagai seorang intelektual publik. Oleh karena itu, perlu dibaca secara lengkap aspek teks dan konteksnya.
Namun, penting untuk diakui bahwa penggunaan bahasa yang kasar dan tidak sopan seperti ini memiliki konsekuensi dan dampak social. Hal inilah yang akhirnya disadari RG. Ia melakukan permohonan maaf sekaligus klarifikasi setelah mencermati gelagak publik. Bagaimanapun bahasa yang merendahkan atau menghina dapat menyulut polarisasi dan memperburuk iklim politik. apalagi masyarakat kita memiliki memori polarisasi semacam itu.
Riak ini terus bergulir, seperti bola salju menggelinding kemana-kemana. Belum lagi algoritma media social lebih cenderung memfasilitasi polemik dibanding bekerja terbalik untuk meredahkan. Joel Osten pernah berkata bahwa “Anda dapat mengubah dunia Anda dengan mengubah kata-kata Anda, tapi Ingat, kematian dan kehidupan berada dalam kekuatan lidah”
Relawan yang Intelektual
Kontroversi posisi kritis RG memberikan pelajaran tersendiri. Ia dikenal sebagai sosok yang berani mengutarakan kritismenya, sekalipun dengan diksi yang kurang elok. Disayangkan karena yang mengatasnamakan diri sebagai relawan dengan percaya diri melontarkan kalimat ; Anj*ng, B*bi, dll, lebih tidak masuk akal adalah persekusi atas pribadi RG. Serangan balik semacam itu alih-alih mencerminkan kedewasaan, justru memperpanjang kegaduhan. Lihat! cara presiden merespon. Ia memberikan contoh atas praktik baik dalam kehidupan berdemokrasi. Hemat saya, presiden menujukkan kualitas kematangannya dengan cara yang elegan.
Dalam percakapan berorientasi politik, penggunaan sarkasme memiliki urgensi tersendiri. Di saat kata bijak tak lagi mengetuk hati, maka sarkasme menjadi penting. Dengan sensitifitas diksinya memungkinkan memiliki efek signifikan. Daripada kata bijak nan sopan tak pernah dihiraukan.
Dalam situasi semacam ini baiknya argumentasi mesti direspon dengan argumentasi. Ada baiknya kita fokus pada konten dan konteks kritik seorang RG. Daripada memberikan ancaman Hukum yang bisa mematikan kritisisme publik. Ada beberapa akun yang mengeritik Rocky karena mengungkapkan fakta yang tidak lagi relevan. Misalnya harga sawit di bawah seribu rupiah. Menurut saya, itu lebih menarik, tentu lebih tepat sasaran dan pasti lebih elegan. Harusnya cara semacam ini bisa jadi model pembelaan bagi siapapun yang mengatasnamakan diri relawan untuk siapapun. Itulah Relawan Intelektual.
Belajar dari Sokrates, Nietzsche, hingga Michel Foucault
Kritsisme dalam banyak lanskap sejarah, seringkali berhadap-hadapan dengan otoritas kuasa. Sokrates, seorang filsuf masa ke emasan Yunani dipaksa minum racun karena berlawanan dengan argumentasi kekuasaan pada saat itu. Galileo Galilei, dan Hypatia adalah deretan nama dalam kisah kelam antara kekuasaan dan kaum intelektual. Sabang hari, Dunia baru menyadari ternyata merekalah yang benar. Namun galibnya sejarah berkehendak lain, mereka dibunuh namun hidup sepanjang masa. Demikianlah sejarah bekerja. Perihnya hidup sebagai Intelektual, Jika tidak dirajam seperti Hypatia, Maka berakhir di tiang gantung seperti Galileo.
Relasi kuasa dengan intelektual adalah kerisauan tersendiri bagi Sosiolog prancis Michel Foucault. Sebagai pemikir kritis, Ia mendorong intelektual memiliki sikap ‘Parrhesia’. Parrhesia diartikannya sebagai sikap berani untuk berbicara, menyampaikan sesuatu yang dianggap benar, meskipun harus menerima konsekuensi sebagaimana yang dialami oleh para intelektual dalam kisah di atas.
Menurut Foucault, bahwa kekuasaan berada di mana – mana. Ia terus beroperasi dalam pengawasan, memberikan alarm pada setiap kritik. Kondisi semacam ini digambarkan sebagai suasana panoptik. Suasana di mana setiap orang merasa dipantau oleh menara kekuasaan. Tepat seperti itu, sebenarnya posisi intelektualitas publik dari masa ke masa termasuk kondisi kita saat ini.
Intelektualitas memang fitrahnya adalah berhadapan dengan otoritas, terkhusus pada otoritas yang menyimpang. Sudah semestinya intelektualitas melakukan panoptifikasi balik kepada kekuasaan. Dialah yang menjadi mata-mata kebaikan dan kebenaran Tuhan di Bumi. Kita mesti belajar dari Foucault, sebagaimana Foucault belajar dari Nietzsche.
Dalam situasi semacam ini, Nietzsche mengajukan satu bentuk moralitas yakni ; Moralitas Dionisyan. Sebuah seruan moralitas yang revolusioner, mendobrak otoritas yang mengekang kebebasan. Nietzsche sama sekali tidak membenci kekuasaan, justru ia mempopulerkan adagium ‘will to power’. Tetapi Baginya, kekuasaan harus mendorong kebebasan, bukan sebaliknya; mengamputasi.
Intelektualisme jangan Selalu Diperhadapkan Hukum
Saat ini, Parrhesia menjadi amat penting sebagai nilai dalam intelektualisme : termasuk dalam kehidupan politik. Melalui nilai itu, kita bisa mendorong para intelektual menyuarakan pandangan kritisnya, tentu berbasis data. Tidak melakukan justifikasi keliru demi memainkan emosi publik. Namun, bagaimanapun seorang intelektual harus bersikap kritis merespon persoalan yang ada. Sekalipun berhadapan dengan kelompok dominan atau otoritas yang ada. Intelektual adalah lilin di tengah kegelapan.
Tentu tidak sulit untuk menyepakati bahwa pengucapan kata itu adalah sala-satu bentuk kekurang-ajaran. Tapi bagaimana kalau kekurangajaran itu diarahkan kepada kekurang-ajaran dengan wajah yang berbeda. Misalnya kekurang-ajaran kekuasaan yang membuat kebijakan tidak memihak pada kepentingan rakyat. Jadi, mana yang lebih kurang ajar?
Terlepas dari seperti apa batas wajar kekurang ajaran itu, penulis tidak dalam kapasitas membela RG sebagai pribadi, tapi mendukung kritisisme, oleh siapapun yang memilih jalan seperti itu. Penulis juga menyayangkan jika posisi kritis sebagai ‘jalan sunyi’ harus terus menerus diperhadapkan dengan masalah hukum. Coba kita lihat begitu banyak yang katanya intelektual dalam kampus, tapi begitu sedikit di antara mereka punya sikap kritis dalam merespon isu atau kebijakan tertentu. Sungguh diamnya kaum intelektual adalah kemunafikan yang paripurna. Intelektual adalah tanda kemanusian jika ia hilang maka tersisalah kebinatangan.
Penulis : Sopian Tamrin (Dosen Sosiologi FIS-H UNM)
Opini ini pernah diterbitkan di Tribun Timur



